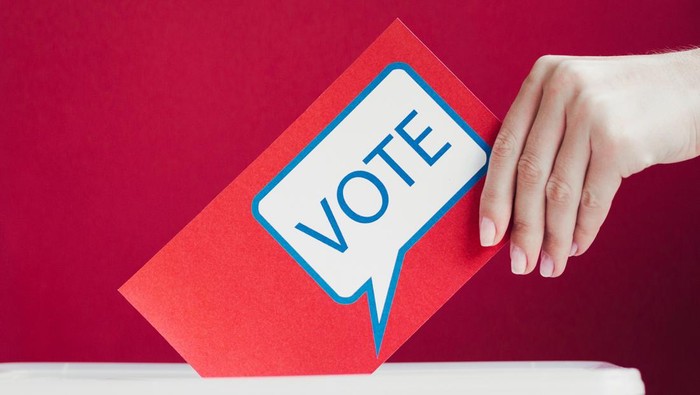Dengan total pemilih mencapai 56 persen, Jawa adalah kunci utama pemenangan pemilu. Temuan Afan Gaffar dalam Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System (1992) terasa masih cukup relevan untuk melihat dan meneropong perilaku pemilih Jawa.
Gaffar menyebutkan perilaku pemilih Jawa banyak dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya, bukan hanya pertimbangan logis atau ideologis. Trisula wajah pemilih yang dikategoresasi Clifford Geertz sebagai abangan, santri dan priyayi.
Para pemilih ini menganut nilai-nilai dan norma seperti rukun, harmonis, dan gotong-royong serta model patron-client relationship yang loyalitas terhadap figur otoritatif pada akar jaringan sosial tradisionalnya. Gaffar menyebutkan legitimasi kultural dan sosial, terutama melalui norma priyayi dan sistem patronase menjadi tekanan budaya dan moral bagi para pemilih.
Gaffar menegaskan perilaku politik pemilih Jawa ini dengan istilah Weber sebagai “the rationality of the irrational”. Sesuatu yang dianggap irasional bagi ilmuwan atau Barat, tetapi dalam logika masyarakat Jawa memiliki rasionalitas tersendiri.
Karena itu, siapa yang berhasil mengadaptasi strategi politiknya dalam sistem sosial dalam bentuk simbol, nilai, dan jaringan sosial akan mampu mengeruk suara mereka. Golkar berhasil menghegemoni kemenangan selama orde baru tidak lepas dari kecanggihan memanfaatkan sistem sosial masyarakat.
Pertanyaannya kini, apakah faktor nilai dan norma kultur Jawa tersebut serta konsep patron-klien masih menjadi determinan utama bagi pemilih Jawa, masih relevan hingga kini?
Lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang melekat dengan sikap masyarakat Jawa yang mengedepankan kerukunan, gotong royong dan harmonis di tengah masyarakat informasi yang berubah (Castells. 2010).
Apakah otoritatif (kiai atau kepala desa) masih relevan dalam masyarakat jaringan dan politik digital kekinian? Maka kemudian, bagaimana digital politik dan politik kontemporer mempengaruhi perilaku masyarakat Jawa. Apakah ada sifat saling melakukan negasi atau disrupsi mengubah menjadi transformasi?
Budaya digital, hegemoni elektoral, patronase lokal dan politik kultural merupakan kombinasi yang menarik untuk meneropong pola-pola pemilih. Tingginya politik uang, tidak lepas dari budaya patronase. Jalur distribusinya tidak lepas dari pengaruh sistem sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Demokrasi telah mengubah konsepsi pemilihan dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Tetapi temuan Gaffar dalam “Javanese Voters” masih cukup berguna dan berkait melihat, mengamati dan menelaah perilaku politik pemilih Jawa yang substansi sosialnya bersangkut paut dengan patron-klien dan nilai harmoni. Konsep nilai dan norma yang kini mengalami ketegangan dengan teknologi informasi.
Rasionalitas kultural yang masih kuat mencengkeram masyarakat Jawa ini sangat menarik jika ditelaah dari sudut pandang masyarakat jaringan Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society (2010). Castells menjelaskan pada era informasi, struktur sosial dan kekuasaan tidak lagi berpusat pada lembaga formal, tetapi tersebar melalui jaringan komunikasi dan arus informasi global.
Dalam penelitian Burhanudin Muhtadi ataupun Edward Aspinall tentang politik uang di Indonesia, kita bisa menikmati menu sajian dari perubahan fungsi dari klientelisme sebagai distributor strategi “politik uang”. Dalam bukunya “Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca‑Orde Baru” (2020), Muhtadi menemukan fakta bahwa proses politik uang, distribusi bantuan sosial dan pemanfaatan tokoh lokal dalam meraup suara menjadi bukti warisan patronase masih melekat.
Artinya, jaringan dan kultur patron-klien tersebut masih hidup, berkembang dan terpelihara dalam konteks politik yang transaksional. Fungsi patron berubah menjadi distributor transaksi politik.
Dalam konteks digitalisasi politik, hubungan patronase berubah dari patronase aktor dan klien menjadi patronase digital. Kekuatan figur masih cukup dominan, meskipun salurannya berubah. Artinya, nilai tradisional yang selama ini melekat masih cukup kuat mengikat, tetapi harus dimediasi dengan jaringan digital.
Figur-figur otoritatif seiring waktu mengalami perubahan, masyarakat ketika mendapati masalah tidak lagi bertanya, meminta nasehat atau pandangan kepada sosok teladan yang selama ini jadi sentral informasi. Melainkan bertanya pada platform komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau TikTok. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik yang dulunya bersifat lokal kini bekerja dalam space of flows yang tak terbatas secara fisik.
Dalam ketegangan antara space of places dan space of flows, pemilih Jawa yang terikat pada ruang waktu tradisional dan terhubung dengan arus informasi beradaptasi sehingga menciptakan hibriditas budaya politik yang baru. Persepsi politik dapat dipengaruhi patron ketika transaksi politiknya jelas, sementara digital politik mengubah persepsi bahwa informasi tidak hanya dapat dicari dari sang patron, tetapi dari media sosial.
Kontinuitas budaya yang melekat masih cukup kuat, tetapi pengaruh modernisasi dan digital politik seakan menginterupsi akar-akar budaya yang menjulang dalam jantung masyarakat. Struktur kekuasaan dan figur otoritatif bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan rasionalitas digital. Ada negosiasi budaya, nilai dan norma di dalam pergulatan tersebut.
Pemilih Jawa adalah contoh konkret bahwa dalam masyarakat jaringan, di mana mereka tetap mempertahankan nilai-nilai budaya. Budaya dan kultur lokal tidak hilang, ia bertansformasi mengikuti arus zaman.
Fakta politiknya, standing position pemilih dari Geertz tentang politik aliran yang terejawantahkan dalam hasil-hasil pemilu tidak banyak berubah. Pergeseran-pergeseran mungkin ada, tetapi etalase hasil politiknya tidak banyak berubah.
Ahan Syahrul Arifin. Mahasiswa S-3 Universitas Brawijaya Malang, Tenaga Ahli di DPR RI.
Lihat juga Video: Kala Cak Imin Pede PKB Rebut Hati Pemilih Jawa Barat di 2024